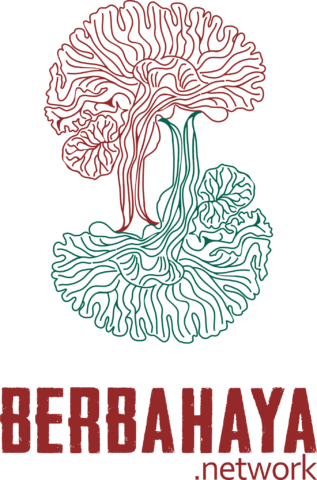Kajian Fotografi Melalui Pendekatan Autoetnografi Pada Penelitian Berbasis Seni
RIDHWAN ERMALAMORA SIREGAR
Berbahaya Network, Jakarta
e-mail: ridhwan.s@pascasarjanaikj.ac.id
ABSTRACT This article focuses on the discussion of the “autoethnography” approach, which is a form of qualitative research that has not been widely found in art study. Research using autoethnog- raphy method is a study that aims to understand certain cultural experiences through self-narrative and personal experiences. Criticism for this method is mainly due to its high subjectivity and lack of analysis, has made autoethnography approach is less popular in Indonesia, especially in pho- tography research.Research that examines visuals such as photography generally uses a semiotic approach, so this paper becomes a pre-eleminary research on the use of autoetnography methods in photography research that I am currently doing. This article departs from a literature review of art- based research, which is still underdeveloped in Indonesia art schools. I am trying to map how au- toethnography method is applied in photography study, so that it can become an alternative method that is academic, valid and analytical in art research.
Keywords: autoethnography; art-based research; photography studies; art-based research
ABSTRAK Artikel ini membahas fotografi melalui pendekatan autoetnografi yang merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang belum banyak ditemukan dalam kajian seni. Penelitian dengan metode autoetnografi merupakan riset yang bertujuan untuk memahami pengalaman budaya tertentu melalui naratif diri dan pengalaman personal. Riset ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui pendekatan berbasis seni (art-based research) pada beberapa foto keluarga. Lewat penelitian ini, penulis mencoba memetakan bagaimana metode autoetnografi digunakan dalam kajian fotografi untuk dapat mengungkap peran dan posisi laki-laki sebagai “ayah rumah tangga”. Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa foto keluarga, didapatkan fakta bahwa ayah selalu tampil pada posisi sentral dan dominan serta sejajar dengan ibu meskipun dalam kesehariannya berperan sebagai “ayah rumah tangga”. Hal itu menunjukkan sekaligus mengukuhkan bahwa posisi dan peran ayah di dalam keluarga sejatinya tidak dapat digantikan oleh siapa pun.
Kata kunci: autoetnografi, kajian fotografi, ayah rumah tangga, penelitian berbasis seni
Pendahuluan
Autoetnografi adalah suatu metode penelitian terhadap manusia yang fokus penelitiannya dilakukan pada diri peneliti sendiri. Dalam autoetnografi, peneliti adalah subjek dan pengalaman peneliti sebagai datanya (Ellis dan Bochner, 2000). Dapat dikatakan bahwa dalam etnografi, peneliti adalah subjek sekaligus objek penelitian. Sejalan dengan itu, Buzard (2003) dan Jackson (2008) memberikan pandangan bahwa autoetnografi merupakan suatu pendekatan alternatif penelitian dan penulisan yang mencari cara untuk mendeskripsikan dan secara sistematis menganalisisis (graphy) pengalaman personal (auto-) untuk memahami pengalaman kultural (etno-).
Meskipun mendapat kritik keras, Sara Delamont dalam tulisannya yang berjudul The Only Honest Thing: Autoethography, reflexivity and Small Crises in Fieldwork yang terbit pada tahun 2009 menyatakan bahwa metode ini mulai banyak dilirik sekitar 15 hingga 20 tahun belakangan. Dalam tulisannya yang lain dengan judul Arguments Againts Auto-Ethnography, Delamont (2007: 2) menyatakan bahwa pada dasarnya metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang “malas”, baik secara harafiah maupun secara intelektual. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa pendekatan autoetnografi merupakan sebuah metode penelitian yang sulit dipertanggungjawabkan keilmiahannya karena sangat sulit untuk memberi jarak pada diri sendiri selaku peneliti untuk tetap netral terhadap pengalaman pribadi peneliti.
Metode autoetnografi memang masih jarang digunakan sebagai sebuah pendekatan. Belum banyak referensi penelitian yang penulis temukan, terutama pada penelitian ilmiah di Indonesia, khususnya pada kajian di bidang seni. Lewat berbagai penelusuran literatur, metode ini sebenarnya dapat menjadi sebuah metode penelitian yang menarik untuk digunakan. Hal itu didasari oleh pandangan bahwa pendekatan ini dapat memberikan ruang yang besar bagi peneliti atau penulisnya untuk mengekspresikan dirinya sendiri terhadap karya yang dihasilkan. Atas dasar itu, dalam penelitian ini, penulis akan membahas foto-foto dan berbagai dokumentasi dengan konteks peran dan posisi laki-laki di masyarakat lewat pengalaman pribadi sebagai “stay- at-home dad” atau biasa disebut sebagai “ayah rumah tangga”. Sebuah istilah yang mungkin masih kurang populer yang coba penulis sematkan pada diri sendiri. Hal itu didasari oleh kenyataan kehidupan pribadi penulis sebagai pekerja independen yang mempunyai banyak waktu di rumah. Sementara itu, istri berperan sebagai pencari nafkah utama di luar rumah.
Autoetnografi dan Penelitian Berbasis Seni
Dalam buku Autoethography as Method dikatakan bahwa autoetnografi memberi ruang dan kesempatan bagi penulis atau peneliti untuk menggunakan suara dan pengalaman pribadinya untuk lebih memahami lingkungan atau situasi budaya yang ada di sekitarnya (Chang, 2008 dan Wall, 2008). Sejalan dengan itu, seorang profesor dalam bidang komunikasi dan sosiologi, Carolyn Ellis (2004) dalam bukunya The Ethnographic I memberi definisi singkat mengenai autoetnografi, yaitu sebagai suatu metode penulisan yang berangkat dari pengalaman pribadi penulis untuk mengamati sensasi fisik, perasaan, pikiran, dan emosi.
Riset berbasis seni sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Sejak lama, seniman telah menggunakan seni untuk menjelajahi sifat dunia dan pengalaman hidup mereka. Selama medio tahun 1970-an, para peneliti ilmu sosial mulai memasukkan penggunaan berbagai bentuk kegiatan artistik dalam pendekatan yang dikenal secara kolektif sebagai penelitian berbasis seni (arts- based research) atau penelitian pendidikan berbasis seni (arts-based educational research) (Leavy, 2009: 229). Leavy yang merupakan seorang peneliti berbasis seni terkemuka menjelaskan bahwa praktik penelitian berbasis seni adalah seperangkat alat metodologis yang digunakan oleh peneliti kualitatif di seluruh disiplin ilmu, termasuk pada semua fase penelitian yang meliputi pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan representasi. Cara-cara yang harus dilakukan, yaitu mengadaptasi prinsip-prinsip seni kreatif untuk menjawab pertanyaan penelitian sosial secara holistik dan saling bersinggungan di mana teori dan praktik saling terkait dan selalu berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, metode berbasis seni mengacu pada tulisan sastra, musik, pertunjukan, tari, seni visual, film, dan media lainnya (Leavy, 2009: 230).
Dalam Art as Experience (1934/2005), John Dewey menyatakan bahwa seni adalah pengalaman yang dihayati dan terdapat ekspresi darinya. Sejalan dengan itu, Elliot Eisner (2008) menyatakan bahwa seni bukan sekadar dekoratif, namun (seni) juga merangsang, menghaluskan, dan menyampaikan makna yang tidak bisa diekspresikan dalam bentuk representasi lainnya. Pengakuan atas tuntutan dan kontribusi seni itu merupakan hal yang sangat penting dalam membenarkan tempat seni di sekolah kita, yaitu sebagai pusat dan bukan sebatas pencapaian pendidikan periferal (Eisner, 2008: 23). Berkaitan dengan itu, dalam beberapa tahun terakhir, peneliti ilmu sosial juga telah mengembangkan bidang terkait autoetnografi dan autoetnografi kritis dalam penelitian seni. Dalam hal ini, penelitian etnografi kelompok budaya dan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan mengeksplorasi pengalaman hidup seseorang sehingga autoetnografi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian berbasis seni apa pun.
Berdasarkan studi literatur dari Art Research International: A Transdisciplinary Journal yang digagas Wang (2017) disebutkan bahwa ada tiga keluarga inti yang membentuk kerangka klasifikasi keseluruhan, yatu penelitian tentang seni, seni sebagai penelitian, dan seni dalam penelitian. Dalam hal ini, keluarga digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana seni dan penelitian dapat saling berhubungan. Selain itu, masing- masing keluarga ini memiliki seperangkat karakteristik khusus dalam hal sifatnya, identitas utama seniman-peneliti, fungsi komponen artistik, bagaimana kaitannya dengan bagian penelitian proyek, dan apa perspektif utama seniman-peneliti. Berikut digambarkan perbandingan antara penelitian tentang seni, khususnya seni sebagai penelitian dan seni dalam penelitian (Tabel 1).
Berdasarkan tabel tersebut, penelitian yang penulis lakukan termasuk ke dalam Art in research. Dalam hal ini, seni dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan penelitian dan menggunakan bentuk-bentuk artistik yang mendukung penyelidikan kualitatif. Penulis menggunakan seni dalam penelitian dan seni secara aktif diterapkan sebagai sebuah proses kreatif dalam satu atau lebih fase proses penelitian. Hal itu diperkuat oleh pandangan Mustaqim (2013) yang menyatakan bahwa paradigma penyelidikan artistik diilustrasikan dengan peranan praktisi sebagai peneliti yang subjektivitas, keterlibatan, dan reflektivitasnya itu diakui dan bahwa pengetahuan harus dinegosiasikan, hasil dari inter-subjektivitas, terikat dengan konteks, dan merupakan konstruksi personal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa objek visual telah menghabiskan banyak energi fisik dan emosional dalam melihatnya dan pastinya hal itu memainkan peran sentral dalam budaya abad ini. Oleh karena itu, disarankan agar tugas meneliti dapat menjadi bagian dari kebutuhan pengalaman, untuk menginspirasi, atau untuk membangun sebuah profesi secara kolektif.
Pendekatan Artistik dalam Autoetnografi
Dalam autoetnografi, hubungan manusia dengan budaya dibahas dalam bahasa ekspresif. Dalam metode yang memadukan personal dan sosial ini, penulis harus menemukan relasi refleksi antara “esensi” dan “budaya”. Selain itu, studi autoetnografi merupakan metode penelitian yang multidimensi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Huriye dan Seniz (2020) yang menyatakan bahwa apa yang membedakan metode penelitian ini dari literatur saat ini adalah adanya kombinasi sains dan seni.
Fotografi, Peran, dan Makna
Fotografi pada umumnya merupakan aktivitas untuk mendapatkan hasil gambar dengan tangkapan kamera. Definisi fotografi menurut Bull (2010: 5), yaitu kata fotografi berasal dari dua istilah Yunani: photo dari phos (cahaya) dan graphy dari graphe (tulisan atau gambar). Maka secara harfiah, makna fotografi adalah kegiatan menulis atau menggambar dengan cahaya.
Dengan pengertian ini, identitas fotografi bisa digabungkan menjadi kombinasi dari sesuatu yang terjadi secara alamiah (cahaya) dengan kegiatan yang diciptakan oleh manusia dengan budaya (menulis dan menggambar/melukis).
Fotografi begitu dekat dengan kehidupan manusia modern saat ini. Bagaimana tidak, lewat adanya teknologi digital, kita bahkan seperti dituntut untuk selalu mendokumentasikan setiap menit hidup kita dan membagikannya di media sosial. Pada dasarnya, fotografi adalah kegiatan merekam dan memanipulasi cahaya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kehadiran teknologi di era digital tentu memberi gambaran bahwa fotografi sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari.
Setiap hari, miliaran foto dihasilkan di seluruh dunia. Manusia mendokumentasikan seluruh kegiatannya, mulai dari pagi hari sesaat setelah bangun tidur, ketika bekerja dan melakukan berbagai aktivitas, hingga sebelum beristirahat (tidur) kembali. Dalam perkembangannya, selain menjadi metode untuk menangkap citra sebuah realitas, fotografi juga merupakan karya visual berwujud citra atau kesan yang berisi informasi atau pesan.
Selain dari segi peralatan, kemudahan-kemudahan teknik pembuatan fotografi juga semakin membuat seorang fotografer lebih berkonsentrasi pada aspek gagasan dan perupaan dibandingkan dari segi teknis. Semua orang kemudian membuat foto dengan adanya kemudahan teknis yang ditawarkan. Dari situ, terjadilah satu bentuk aktivitas komunikasi dan bercerita lewat gambar. Bahkan, fotografi juga dapat memprovokasi dan membentuk cara pandang baru, sekaligus mengajak orang untuk bertindak. Lebih jauh, fotografi memiliki peran besar dalam mengomunikasikan suatu citra pada masyarakat. Ketika sebuah foto diproduksi, ia akan menjadi produk sosial dari masyarakat tersebut. Tidak hanya itu, foto juga dapat menjadi sebuah produk yang digunakan untuk mengomunikasikan banyak hal, di antaranya adalah penyampaian makna-makna dan berbagai kepentingan sosial sesuai dengan latar belakang dan motif pembuatan foto itu.
Saat ini, fotografi semakin banyak diminati dan semakin dilihat peran dan maknanya secara sosial kultural. Perkembangan fotografi dalam sejarah bukan hanya soal perubahan teknologi, melainkan juga perubahan kultural. Foto menjadi alat perubahan sosial sekaligus mampu membawa cara pandang baru bagi masyarakat dalam memaknai hidup. Dalam kasus ini, ada pergeseran paradigma konsep fotografi dari yang semula hanya berfokus pada “elemen dalam”, lalu berkembang juga analisis terhadap aspek “konteks luar”, yakni makna atau peran kulturalnya (Bornok & Setiawan, 2015). Namun demikian, fotografi bukan hanya sebagai produk kultural, melainkan juga dapat memproduksi kultur. Hal ini sejalan dengan gagasan-gagasan David Bate dan Stephen Bull tentang fotografi yang menyatakan bahwa paradigma pemikiran kritis tentang fotografi bergeser ke arah kultural dengan fokus penelaahan pada makna fotografi bagi pengalaman hidup manusia.
Foto: Media Eksplorasi dan Ekspresi Interpretasi
Dalam konsep “Culture is Ordinary” yang digagas oleh Raymond Williams (1958) disebutkan bahwa segala aspek kehidupan manusia, baik dalam rupa tindakan, benda-benda material, ide atau gagasan, maupun pemikiran manusia termasuk ke dalam kebudayaan. Mulai dari hal yang bersifat remeh-temeh sampai pada hal-hal yang bersifat kompleks dan berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, termasuk soal kebudayaan.. Dari definisi Williams tersebut, segala aspek kehidupan manusia tadi dapat dimaknai juga sebagai suatu gejala kebudayaan, yaitu sebagai bentuk representasi dan praktik kehidupan sehari- hari yang dapat diamati maupun dipelajari oleh masyarakat, termasuk di dalamnya fotografi.
Edwards (2002: 67-75) pernah mengemukakan gagasannya tentang cara menampilkan diri dalam berbicara tentang materialitas foto. Ahli ini menyatakan bahwa pengalaman kita dalam memotret, menurut pengamatannya, terletak dalam ruang dan waktu serta dimediasi oleh format presentasi dan konteks tampilan. Dengan demikian, foto itu sejatinya dapat membawa makna bahkan sebelum seseorang mempertimbangkan konten gambar. Edwards dan Hart (2004) menyoroti ini dengan deskripsi dari Roland Barthes tentang sebuah foto, yaitu yang pertama dan terutama adalah tentang materialitas objek dan baru kemudian menyertakan referensi ke gambar yang sebenarnya. Selanjutnya, Edwards menyarankan bahwa kita juga perlu membahas materialitas lain yang belum terdepan dalam konsentrasi studi visual pada aspek semiotik dan representasi foto. Sejalan dengan itu, menurut Edwards (2002) materialitas terkait erat dengan biografi sosial dan objek apa pun harus dipahami sebagai bagian dari proses makna, produksi, pertukaran, dan penggunaan yang berkelanjutan.
Foto sebagai Refleksi dan Naratif Diri
Isu seputar peran foto sebagai dokumen terletak pada adanya kepercayaan bahwa foto adalah medium perekaman visual objek atau peristiwa yang autentik, akurat, netral, dan objektif. Sudarma (2014: 2) memberikan pengertian bahwa media foto adalah salah satu media komunikasi, yakni media yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau ide kepada orang lain. Namun, di era post-modernisme, foto tidak hanya dipandang sebagai medium untuk merekam kenyataan, tetapi juga sebagai suatu medium kultural yang membawa muatan-muatan ideologis yang sering kali begitu halus dan manipulatif (Setiawan dan Bornok, 2015: 31). Aktivitas fotografi tidak bisa didasarkan hanya pada kegiatan tentang bagaimana cara memotret saja. Namun, fotografi juga harus disertai dengan seni (Gani dan Kusumalestari, 2014: 4). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa fotografi sebenarnya merupakan teknik yang digunakan untuk mengabadikan momen penting dalam kehidupan.
Dalam sebuah penelitian tentang album foto keluarga, Hirsch (1997) menyatakan bahwa “melangkah ke dalam visual bukan untuk terlibat dalam teori sebagai penjelasan sistematis dari serangkaian fakta, tetapi untuk mempraktikkan teori, untuk membuat teori seperti halnya fotografer secara material membuat gambar” (Hirsch, 1997: 15 dalam Knowles dan Cole, 2007: 258). Sesuatu yang menarik dalam penelitian tersebut bahwa menurut Hirsch, banyak peserta dalam proyek album foto tersebut menemukan perspektif baru ini pada foto domestik mereka yang diakui dalam situasi akademis sebagai tantangan, pembebasan, dan ekspansif. Hal itu seperti menunjuk mereka ke halaman belakang diri mereka sendiri, yakni sumber materi yang sering diabaikan. Lebih lanjut, Hirsch (2002) menjelaskan bahwa mereka memahami “studi dapur” yang dapat mengurangi beberapa masalah etis. Hal ini membebaskan mereka untuk berpikir secara berbeda tentang kehidupan mereka sendiri dengan cara yang kompak, namun konkret.
Masih menurut Hirsch, ia pernah mengungkapkan tentang bagaimana foto keluarga sebagai sebuah naturalisasi dari praktik kebudayaan sesungguhnya dapat menyamarkan “stereotip dan karakteristik kode mereka” (Hirsch, 1997: 7). Penelitian terhadap album foto sebenarnya seperti “mengeluarkan” seseorang yang berada dalam foto keluarga dari konteksnya dan memaksanya untuk keluar dari keluarga dan genre personal untuk mengakui praktik budaya yang tertanam di masyarakat. Hal itu dilakukan agar seorang peneliti dapat mengidentifikasi perubahan melalui objek dan ritual yang ada di foto. Hal semacam ini adalah representasi dari sudut pandang yang menuntut peneliti “menjauh” dan berjarak. Proyek penelitian ini juga sekaligus memperjelas apa yang disebut Hirsch sebagai aspek “pribadi, akrab, dan hampir tidak terlihat” dari foto-foto keluarga, kemudian membawanya ke dalam konteks sosial yang lebih luas di mana mereka diambil, dilestarikan, dan dilihat (Hirsch, 1997:10).
Gaya dalam penelitian seperti yang dinyatakan Hirsch itu secara pendekatan serupa dengan proyek-proyek foto personal yang penulis buat dalam beberapa tahun ke belakang. Dalam berkarya, penulis cenderung tertarik untuk mengangkat tema keseharian dan mengenai isu-isu personal dalam keluarga. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menyertakan foto-foto keluarga sebagai data dalam penelitian ini.
Merancang Cara Penelitian
Topik yang diinvestigasi melalui penelitian autoetnografi yang penulis rencanakan adalah demonstrasi dari studi berbasis gambar kritis serta penyelidikan otobiografi melalui bentuk “kerja memori” (Kuhn, 1995: 200). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendekonstruksi peran gender yang penulis pelajari melalui ingatan yang dipicu oleh sebuah foto. Hal lain yang juga penting untuk penelitian ini adalah menekankan bahwa foto dan artefak serupa lainnya tidak hanya mendokumentasikan peristiwa dan orang, tetapi juga secara aktif membangun ingatan dan menciptakan makna. Selanjutnya, ingatan pribadi dibentuk dalam konteks sosial-budaya yang lebih besar dan perilaku yang dipelajari secara sosial dapat menyatukan pribadi, sosial, dan sejarah (Kuhn, 2000: 179). Ingatan kita akan membentuk identitas kita dan dapat menempatkan kita sebagai anggota keluarga dan komunitas yang lebih luas dalam hal ini, misalnya berkaitan dengan komunitas kelas, gender, dan bangsa (Kuhn, 2000: 179). Atas dasar itu, tulisan ini merupakan penelitian autoetnografi terhadap pengalaman diri sendiri dan bagaimana pengalaman dan perjalanan hidup diri itu ikut membentuk pandangan dan sikap hidup penulis saat ini.
Seperti yang ditulis Kuhn (1995: 8), kerja ingatan terjadi baik di masa lalu maupun di masa kini. Pekerjaan itu tidak pernah berakhir, tidak mengungkapkan kebenaran tertinggi, tetapi justru menambah pengetahuan yang lebih besar dan pemahaman baru tentang masa lalu dan masa kini. Hal ini mungkin akan menjadi interpretasi awal dan membantu peneliti untuk memahami karya ilmiah dan seninya serta motif dalam melakukannya. Sebagai contoh, dalam rencana penelitian yang akan dilakukan, penulis mencoba memahami betapa besarnya pergeseran peran penulis sebagai laki-laki membuat penulis harus mendefinisikan ulang diri sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan keluarga penulis dan mempertanyakan semua yang pernah dialami sebelumnya. Smith (1998) pernah menyatakan bahwa rasa diri sebagai identitas berasal secara paradoks dari hilangnya kesadaran fragmen sejarah pengalaman (Smith, 1998: 108). Perubahan radikal dalam hidup penulis mendorong diri penulis untuk menemukan “suara” untuk pertanyaan ini (Kuhn, 1995:103). Dengan autoetnografi, penulis berusaha mencari bahasa dan ruang dalam batasan akademis yang memungkinkan penulis untuk menceritakan kisah sendiri dari perspektif pribadi. Seorang laki-laki, kepala keluarga, suku batak, dan mungkin juga dari segi agama.
Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa sebagai sebuah pendekatan, autoetnografi memiliki posisi sendiri dalam suatu rancangan penelitian. Autoetnografi memiliki kompleksitasnya sendiri dalam memandang suatu permasalahan, baik itu identitas, kehidupan, relasi, maupun pengalaman personal seseorang. Atas dasar itu, untuk bisa mengungkapkan hal-hal tersebut dalam suatu rencana penelitian, tentu bukanlah perkara mudah. Suatu desain penelitian autoetnografi yang diharapkan bisa mengungkapkan kompleksitas-kompleksitas itu, tidak dapat hanya dengan menggunakan rancangan penelitian yang berupa eksperimen, survei, atau daftar pertanyaan seperti umumnya ditemukan pada penelitian kualitatif lain. Namun, Adams, Jones, dan Ellis (2015: 26) menyatakan bahwa autoetnografi juga harus memiliki beberapa hal yang menjadi prioritas, perhatian, dan cara-cara dalam melakukan penelitian yang meliputi:
- Mengedepankan pengalaman pribadi dalam penelitian dan penulisan;
- Menggambarkan proses pembentukan makna;
- Menggunakan dan menunjukkan refleksivitas;
- Menggambarkan pengetahuan dari orang dalam (insider) dari suatu fenomena budaya atau pengalaman;
- Mendeskripsikan dan mengkritisi norma budaya, pengalaman, dan kebiasaan;
- Mencari respons dari pembaca.
Dalam penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana melakukan penelitian autoetnografi, Chang (2008) mencoba menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan baik itu sebelum maupun saat melakukan penulisan autoetnografi itu sendiri. Salah satu hal yang ditekankannya dalam penulisan autoetnografi adalah mengumpulkan data kenangan.
Implementasi Metode Autoetnografi
Ketika seorang autoetnografer bernama Patricia Leavy (2009) mengajar di Stonehill College di Easton, Massachusetts, dia menggunakan sejumlah pendekatan penelitian berbasis seni sebagai seperangkat alat pedagogis untuk mengajarkan literasi media dalam kursus sosiologi sarjana berjudul Images and Power: Popular Culture. Leavy menyatakan bahwa dia memasukkan penelitian berbasis seni ke dalam mata kuliahnya sebagai bagian dari pendekatan holistik dan partisipatif terhadap literasi media. Praktik berbasis seni adalah alat yang efektif untuk mengembangkan kesadaran kritis (Leavy, 2009: 225). Leavy mempunyai tujuan, yaitu agar muridnya memahami lebih dalam tentang kekuatan sosial dan bagaimana hal itu bekerja melalui ideologi dan memengaruhi kehidupan psikis individu. Menurutnya, kesadaran kritis yang tinggi adalah prasyarat yang diperlukan untuk refleksivitas semacam ini.
Berangkat dari pengetahuan yang didapatkan dalam pencarian tentang bagaimana cara mengaplikasikan autoetnografi, lalu penulis mulai mencari berbagai macam data yang akan menjadi bahan analisis, kemudian mempraktikkannya. Penulis menggunakan teori-teori fotografi untuk membantu penulis dalam melakukan analisis kritis dan interpretasi data, terutama yang berhubungan dengan keberaksaraan visual (Ajidarma, 2001: 26). Dalam hal ini, berbahasa bisa diandaikan sebagai produk pikiran, lalu pada gilirannya menjadi produk kebudayaan, kemudian tercipta wahana pengetahuan. Hal itu juga berlaku pada penghadiran gambar-gambar. Selain lewat analisis kritis, proses kreatif sebagai kekhasan dalam penelitian berbasis seni juga penting dilakukan, seperti memotret dan menulis bebas. Dalam hal ini, tentunya sesuatu yang berhubungan dengan konteks penelitian, misalnya dengan penyajian artefak atau dokumen pendukung lain, baik milik pribadi, milik keluarga, maupun milik publik, seperti foto-foto keluarga. Hal itu sejalan dengan penggunaan memori dalam autoetnografi Kuhn:
“Family photographs may affect to show us our past, but what we do with them—how we use them— is really about today, not yesterday. There can be no last word about my photograph, about any photograph” (Kuhn, 1995:16).
Lewat data berbagai foto keluarga, penulis mendapatkan gambaran bahwa keberadaan ayah (laki-laki) hampir selalu tampak dominan atau sering kali posisinya sejajar dengan istri. Bahkan, hal itu juga terjadi pada keluarga yang menganut paham matrilineal sekali pun dan pada status sosial ekonomi apa pun. Dari sini, bisa terlihat bahwa selain dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat, ayah memang selalu digambarkan mempunyai posisi sentral atau paling kuat dalam keluarga, bahkan tercermin dalam banyak foto keluarga pada umumnya. Hal ini sejalan dengan peran dan posisi ayah, yaitu sebagai pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga.
Potensi Refleksifitas pada Metode Autoetnografi
Foto di atas merupakan salah satu foto dari rangkaian seri foto (mencari) amang, yaitu sebuah monograf yang penulis buat setelah berpameran tunggal untuk pertama kalinya. Proyek foto ini dibuat setelah penulis akhirnya memutuskan berhenti bekerja dan kemudian ikut menemani istri bersekolah. Saat itulah, untuk pertama kali, penulis benar-benar tinggal bersama dengan anak dan istri setelah sekitar 3 tahun sebelumnya tinggal terpisah. Dalam proyek ini, penulis mendokumentasikan momen- momen berharga dalam perkembangan anak penulis selama hampir 2 tahun. Hal yang sebelumnya tidak sempat dan jarang penulis lakukan. Secara umum, di dalam masyarakat, para ayah sesungguhnya memang memiliki waktu yang terbatas untuk bermain bersama anaknya, terutama karena mereka sibuk bekerja.
Pada saat itu, perasaan campur aduk muncul ketika mendengar kabar istri penulis mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Universitas Columbia, New York. Di satu sisi, penulis merasa senang karena perjuangannya berhasil. Di sisi lain, muncul rasa takut karena jika ikut berangkat, penulis yang tentunya akan mengurus anak sementara istri menempuh pendidikan. Sebagai laki-laki, tentu ada perasaan cemas dan takut karena terbayang karier istri akan lebih baik dari pada karier penulis sendiri.
Penulis terus-menerus dihadapkan pada dilema ketika menulis tentang diri sendiri dalam konteks keluarga dengan subjektivitas yang tinggi. Kegiatan mengevaluasi kembali identitas seseorang secara kritis dalam batas- batas yang telah ditentukan sebelumnya bukanlah tugas yang mudah, apalagi menyangkut diri sendiri. Sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga penulis bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Ketika penulis memutuskan untuk berhenti bekerja dan menemani istri bersekolah, penulis merasa liyan. Untuk mengambil keputusan tersebut, penulis terus mengalami dilema karena penulis menjadi anak pertama dalam tiga generasi yang mengambil keputusan tersebut. Oleh sebab itu, salah satu kendala yang penulis hadapi adalah masih ada perasaan kurang nyaman dan rasa terganggu ketika harus menganalisisis data foto dengan pendekatan autoetnografi.
Setelah karya pertama, “(mencari) amang” selesai, penulis kemudian tertarik untuk mengangkat isu-isu sosial tentang keluarga. Penulis mengeksplorasi sebuah tema lain yang juga menjadi perhatian penulis dalam sebuah proyek berjudul “stay at home dad” atau “ayah rumah tangga”. Sebutan ayah rumah tangga sendiri belum lazim digunakan di Indonesia dan di Asia karena negara-negara di Asia sangat kental dengan kultur patriarkinya. Tugas mengurus anak di rumah pada umumnya dilakukan oleh seorang ibu. Selain dari segi tradisi, stigma ayah rumah tangga juga kerap dikaitkan dengan ajaran agama. Tidak heran apabila ada pria yang mau melakoni peran ini, dia akan sering mendapat stigma negatif dan dipandang sebelah mata. Sementara itu, dalam budaya di banyak negara barat, konsep laki-laki dalam keluarga relatif sama dengan wanita.
Beberapa tahun belakangan, konsep tentang ayah rumah tangga terus menjadi perbincangan. Saat ini, mulai banyak ditemui pasangan yang bertukar peran. Aktivitas mengurus anak di rumah dan menyiapkan keperluan rumah tangga sudah cukup banyak diambil alih oleh suami. Sementara itu, istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah. Berangkat dari hal tersebut, penulis kemudian juga memotret keseharian Ichak. Beliau adalah seorang desainer grafis. Istrinya, Pipin, adalah seorang arsitek. Namun, Ichak bertanggung jawab untuk urusan rumah tangga selama Pipin di kantor. Ichak dan Pipin memang sudah sepakat bahwa tidak ingin anaknya, Ala, dijaga oleh orang lain.
Penulis mencoba mengambil jarak dari gambar ini dan menganalisisisnya. Dari gambar ini, penulis mencari cara untuk menjelaskan perasaan penulis saat ini terhadap keluarga sendiri. Penulis mencoba untuk mengambil benang merah gambar tersebut untuk menemukan korelasinya dengan kehidupan penulis sendiri. Kisah keluarga yang ditimbulkan oleh memori atau foto itu telah membuat penulis merasa menjadi bagian dari sekelompok orang yang hidup seperti Ichak. Dari data foto keluarga Ichak, dapat dilihat bahwa ayah dan ibu sejajar posisinya. Sama halnya dengan posisi ayah dan ibu pada beberapa foto keluarga yang sudah penulis bahas sebelumnya. Namun, perlu diketahui juga bahwa di dalam keadaan sebenarnya, Ichak yang merupakan seorang pekerja lepas memiliki penghasilan yang tidak tetap. Berbeda dengan Pipin yang bekerja pada sebuah perusahaan sebagai arsitek. Penulis mencoba untuk mencari kemiripan situasi ini dengan pengalaman pribadi penulis. Akan tetapi, hal itu juga membuat penulis mempertanyakan kembali peran dan posisi penulis dan setiap orang dalam cerita ini.
Dalam konteks “ayah rumah tangga”, penulis ingin menyampaikan bahwa menjadi bapak rumah tangga tidak selalu terjadi karena faktor keadaan yang mengharuskan mereka berhenti atau tidak bekerja di kantor. Adakalanya, “ayah rumah tangga” menjadi konsep pilihan yang diputuskan bersama dalam sebuah keluarga, seperti yang terjadi dalam keluarga Ichak. Meskipun menjadi bapak rumah tangga, tidak berarti sang suami sama sekali tidak bekerja. Saat ini, banyak pekerjaan yang memperbolehkan seseorang bekerja dari rumah, misalnya seorang fotografer seperti penulis, desainer, seniman, dan banyak lagi profesi lainnya. Cerita tentang Ichak merupakan “suara” penulis yang dalam keseharian juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak. Sementara itu, sang istri menjadi pencari nafkah utama. Cerita tentang “ayah rumah tangga” adalah cara penulis untuk mengkonfrontasi stereotip dalam masyarakat terhadap laki-laki yang lebih banyak di rumah.
Eakin (1999) berpendapat bahwa hubungan interaktif individu dengan orang lain (terutama keluarga) dan lingkungan hidupnya adalah komponen kunci untuk memahami individu. Penulis tidak ingin membawa peran yang penulis “ciptakan” itu ke dalam struktur keluarga besar. Sebaliknya, melalui autoetnografi, penulis juga ingin memberikan perspektif dan pemaknaan lain terhadap laki-laki dengan cara menjadi subjek, dengan menulis kata- kata, dan dengan membaca ulang foto-foto yang relevan dengan pengalaman penulis. Tindakan itu juga tentu saja memungkinkan terjadinya kesalahan dalam membaca atau menafsirkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kejelian dan kekritisan dalam mengungkap makna dalam setiap foto serta memberi jarak secara personal dan emosial dalam membongkar data tersebut.
Simpulan
Dari paparan pada bagian sebelumnya, tanpa sadar kita sering menafsirkan, membuat, dan menggunakan gambar dan juga menggunakan kode-kode dan konvensi sosial lewat pengalaman personal. Dalam hal ini, fotografi mempunyai status istimewa sebagai sebuah pesan tanpa kode yang dapat memberikan pesan secara berkesinambungan. Pemahaman akan pemaknaan visual dapat membantu kita untuk mengadopsi pandangan orang lain dan melihat sudut pandang lain dengan cara meminjam pengalaman mereka. Hal ini juga memungkinkan terjadinya perbandingan antara pandangan orang lain dengan pengalaman pribadi. Lebih lanjut, dengan mengekspos ingatan yang paling pribadi ke dalam analisis naratif, seorang autoetnograf dapat membiarkan ingatan masa lalu, harapan masa depan, mimpi, ketakutan, dan keinginan terus terjalin dan saling terhubung. Kenangan, ingatan, dan pengalaman dari diri penulis sendiri menjadi suatu hal penting dalam penulisan autoetnografi. Meskipun ada kritik dan perdebatan, metode autoetnografi dapat menjadi warna baru dalam penelitian bidang seni, terutama untuk kajian seni visual, khususnya fotografi. Selain itu, autoetnografi juga dapat menjadi alternatif pilihan metode penelitian yang “berbeda” karena selain menjadi subjek penelitian, seorang penulis (peneliti) juga sekaligus dapat menjadi objek.
Daftar Rujukan Buku
Adams, T. E., S. Holman Jones S., dan C. Ellis. 2015. Autoethnography. New York, NY: Oxford University Press.
Ajidarma, Seno Gumira. 2003. Kisah Mata: Fotografi Antara Dua Subjek, Perbincangan tentang Ada. Yogyakarta: Galang Press
Bull, Stephen. 2010. Photography. Oxon: Routledge.
Chang, Hewon. 2008. Autoethnography as a Method. California, Left Coast Press, Inc.
Edwards, E. 2002. Material Beings: Objecthood and Eethnographic Photographs. Visual Studies, 17(1), 67–75.
Edwards, E., & J. Hart (Eds.). 2004. Photographs, Objects, Histories on the Materiality of Images. New York: Routledge.
Eisner, E. W. 2002. The Arts and the Creation of Mind. New Haven & London : Yale University Press.
Ellis, C. 2004. The Ethnographic I: A Methodological Novel About Autoethnography. Walnut Creek, CA: AltaMira Press/Rowman & Littlefield.
Gani & Kusumalestari. 2014. Jurnalistik Foto : Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Hirsch, M. 1997. Family frames: Photography, Narrative, and Postmemory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hirsch, M. 1999. Introduction: Familial Looking. In M. Hirsch (Ed.), The Familial Gaze (pp. xi-xxv). London: University Press of New England.
Leavy, P. 2009. Method Meets Art: Arts- Based Research Practice. New York, NY: Guilford Press.
Kuhn, A. 1995. Family Secrets: Acts of Memory and Imagination. New York: Verso.
Kuhn, A. 2000. A Journey Through Memory. In S. Radstone (Ed.), Memory and Methodology (pp. 179-196). New York: Berg.
Smith, S. 1998. Performativity, Autobiographical Practice, Resistance. In S. Smith & J. Watson (Eds.), Women, Autobiography, Theory: A Reader (pp. 108-115). Madison: University of Wisconsin Press. (Original work published 1995)
Sudarma, I Komang. 2014. Fotografi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Williams, R. 2011. Culture is Ordinary. New York: Verso
Jurnal
Buzard, J. 2003 “On Auto-Ethnographic Authority”. The Yale Journal of Criticisim 16(1), 61-91
Delamont, Sara. 2007. “Arguments againts Auto-Ethnography”. Quality: 2-4
Delamont, Sara. 2009. “The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork, Ethnography and Education”
Ellis, C., Adams, T. E., Adams & Bochner, P. 2011. “Autoethnography: An overview”. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 10. Retrieved from http://www. qualitative-research.net/index.php/ fqs/article/view/1589/3095. (Diakses pada 20 Januari 2020, pukul 14.00 WIB)
Mustaqim, Karna; Adiwijaya D. Rio, dan Indrajaya Ferdinand. 2013. “Penelitian Atas Penelitian Seni dan Desain: Suatu Studi Kerangka Filosofis-Paradigmatis bagi Penelitian Seni dan Desain Visual”.
Setiawan, Rudi & Bornok, Mardohar Batu. “Estetika Fotografi”. Shakka, Anne. 2020. “Berbicara Autoetnografi: Metode Reflektif Dalam Penelitian Ilmu Sosial”. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya 14, No. 1.
Varto, J. 2009. “Basics of Artistic Research: Ontological, Epistemological and Historical Justifications”. University of Art and Design Helsinki.
Wang, Q., Coemans, S., R. Siegesmund, dan K. Hannes. 2017. “Arts-based Methods in Socially Engaged Research Practice: A Classification Framework. Art/Research International: A Transdisciplinary Journal”, 2(2), 5–39. https://doi. org/10.18432/R26G8P (Diakses pada 15 Januari 2020, pukul 16.00 WIB).
Tesis/Disertasi
Dethloff, Carl Henry. 2005. “A Principal In Transition: An Autoethnography”, Disertasi Ph.D, Educational Administration, Texas A&m University.
Guyas, Anniina Suominen. 2003. “Writing With Photographs, Re- constructing Self- An Arts-based Autoethnographic Inquiry”. Disertasi Ph.D, Art & Education Department, Ohio University.
Ownby, Terry D. 2011. “Wunderkammers, Photographs, And Growing Up Southern: A Visual Semiotic Analysis Of Self-Identity Through Autoethnography”. Disertasi Ph.D School of Education, Colorado State University.
Shakka, Anne. 2017. “Cilik-Cilik Cina, suk gedhe meh dadi apa? Sebuah Studi Autoetnografi Mengenai Pengalaman Rasisme”. Tesis Magister Ilmu Religi Dan Budaya, Sanata Dharma.