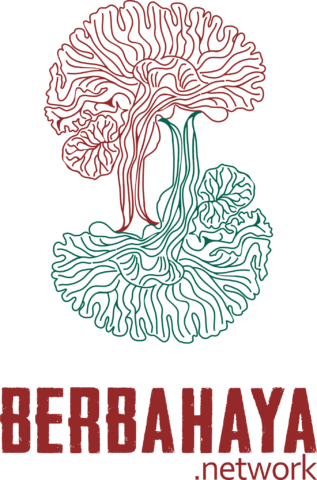Dewi Nur ‘Kartini’

Oleh: Ridhwan Siregar
“Foto yang baik itu adalah yang bisa membawa perubahan.” Saya ingat, hal itu dikatakan Dewi Nurcahyani, suatu malam di Hanoi, Vietnam, sekitar akhir Oktober 2017. Cukup lama saya mengenal ‘Tante Dewi’, biasa saya memanggilnya. Dia adalah seorang fotografer perempuan energik, yang telah menjalani profesinya selama hampir dua puluh tahun. Karyanya telah banyak menghiasi berbagai media, baik lokal maupun internasional. Lewat fotografi, Dewi telah mengubah kehidupan banyak orang.
Sejak belia, kamera telah mencuri perhatian Dewi, anak tengah dari tiga bersaudara, asal Madiun, Jawa Timur. Dari tingkat sekolah dasar, ia sudah mulai hobi memotret, dan berlanjut terus hingga sekolah tingkat atas. “Lulus SMA baru belajar fotografi beneran,”, ujarnya. Kemudian Dewi menjadi fotografer untuk majalah Karnisa, sebuah media dari Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, Solo, tempat ia nyantri.
Keseriusan Dewi dengan fotografi, terus berkembang. Namun saat itu, niatan untuk terus mendalami fotografi, tak disambut baik oleh Ayahnya. “Mau jadi apa nanti? Tukang foto itu nggak ada masa depannya”, cerita Dewi pada saya ketika mengingat momen saat dia meminta restu untuk meneruskan kuliah di Visi Art and Graphic Design School, Yogyakarta. “Mungkin Bapak membayangkan tukang foto keliling, yang setelah motret orang, dibayar terus ditinggal kabur. Memang pernah ada sih yang seperti itu di kampungku dulu”, kenang Dewi, yang memang suka bercanda.
Saat itu, ayahnya menyarankan Dewi untuk sekolah memasak, karena dianggap menuruni bakat neneknya. Dewi pun terpaksa berbohong, lalu sekolah diam-diam, mengambil Diploma jurusan Desain Grafis, dengan konsentrasi utama fotografi. “Bapak hanya tahu, di Jogja aku belajar bahasa Inggris di LIA, padahal aku juga kuliah di Visi”, cerita Dewi.
Peran kakak kandung Dewi, Ratna Listy, sangat besar dalam keputusannya. Kakaknya lah yang membiayai sekolah, juga membelikan kamera, sebuah Nikon FM10. Berbekal semangat, dan dukungan besar Ratna, Dewi kemudian lulus. “Bapak baru tahu aku sekolah di VISI, saat lulus setahun kemudian. Beliau menangis terharu”, kenang Dewi, mengingat masa kuliahnya.
Selesai kuliah, fotografi jurnalistik menjadi pilihan Dewi. Harian Rakyat Merdeka, menjadi tempat awal Dewi dalam memulai karier profesionalnya di awal tahun 2000. Waktu itu, belum banyak perempuan yang memilih profesi yang sebagian besar dijalankan oleh pria. Dewi berkata, “Sebagai fotojurnalis, di lapangan 99% fotografer adalah laki-laki. Yang jelas, mental harus lebih tebal, karena kita tidak bisa dianggap perempuan (apalagi manja) kalo sudah di lapangan. Semua sama. Aku tunjukkan kalo karyaku gak kalah dengan laki-laki.”
Tak sampai dua tahun, karirnya menanjak. Dewi loncat ke Harian Kriminal Lampu Merah, didapuk merangkap sebagai editor foto, hingga pertengahan 2002. Bekerja di ‘Lampu Merah’ meninggalkan kesan mendalam. Tak hanya berbaur dengan laki-laki, tapi Dewi juga bergaul dengan para preman dan penegak hukum. Yang difoto pun bukan hal biasa. Mulai dari mayat berbagai bentuk, sampai demo yang penuh bom molotov. “Hampir setiap hari pulang bau mayat, atau muka penuh odol jika abis motret demo”. Semua dijalaninya dengan senang. “Karena pada dasarnya, aku suka tantangan,” imbuh Dewi.
Namun, akibat foto-foto yang dihasilkannya yang membuat Dewi memutuskan mundur kemudian. “Aku sudah mulai error, karena doanya jadi buruk terus setiap hari. Masa tiap hari aku berdoa harus ada mayat, harus ada kecelakaan, harus ada bencana. Kalau nggak, kan gak ada foto.”, kenang Dewi sambil tertawa.
Selesai bertugas di Lampu Merah, Dewi sempat beberapa bulan bekerja di Darwis Triadi Photography. Dia kemudian pindah ke majalah Muslimah, sebelum berlabuh di majalah Paras. “Bekerja di majalah bertema lifestyle, membuat saya lebih sering berhadapan dengan model dan studio. Yang difoto cantik-cantik dan wangi-wangi. Bukan demo dan jalanan lagi. Tapi memang itulah foto jurnalis, harus bisa memotret apapun dalam keadaan bagaimanapun”.
Memotret model dan artis menjadi pekerjaan sehari-hari Dewi, saat bekerja untuk majalah Paras. Ia bekerja di studio, namun tak jarang juga harus mendatangi rumah ‘sang artis’ untuk pemotretan, dengan membawa peralatan studio yang berjibun. Beberapa kali orang-orang yang ia foto tidak menyangka Dewi adalah ‘sang fotografer’.
“Kejadian yang sering membuatku speechless adalah ketika usai setting lampu dan tinggal menunggu make-up artist menyelesaikan tugasnya, sering ada pertanyaan, ‘fotografernya belum datang ya mbak?’.”, kata Dewi mengenang. Di Paras, Dewi bertahan selama 12 tahun, sebelum memutuskan bekerja freelance.
Bekerja freelance mengasah kepekaan Dewi bercerita lewat foto. Dengan tantangan sebagai pekerja lepas yang berat, kelihaian Dewi justru semakin terlihat. Karyanya kerap jadi viral, di media sosial. “Kalau akhirnya jadi viral, kayanya itu Tuhan yang atur. Aku gak pernah mengira, ga k berharap juga. Yang jelas aku motret sesuatu yang harus aku kabarkan kepada masyarakat”, kata Dewi. Bersenjatakan kamera, dia kerap membuat perubahan bagi orang-orang yang menjadi objek bidikannya.
Salah satunya adalah Turinih atau karib disapa Ninih, seorang penjual gethuk, penganan khas Jawa, yang kerap mangkal di sekitar kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terkesan dengan wajah Ninih yang menarik, Dewi mengungah foto Ninih ke dunia maya. Akibatnya, Ninih jadi terkenal. Hidup Ninih pun berubah drastis, karena mendadak menjadi artis. Lainnya adalah Getun, seorang anak tuna daksa. Potret Getun yang terbit di berbagai media internasional, membuat banyak pihak menjadi bersimpati, dan tergerak untuk membantunya. Meski tidak jarang juga, foto karya Dewi menimbulkan pro dan kontra di media sosial.
‘Kehebatan dalam mengubah’ mungkin kekuatan Dewi. Namun ada hal yang saya harap tak diubahnya sampai kapan pun, yaitu keceriaannya. Dewi adalah seorang penyintas kanker. Ia divonis kanker rahim pada 2005, dua tahun setelah menikah dengan Luhur Hertanto, yang juga seorang jurnalis. Penyakit itu memang telah mengubah kemampuan tubuhnya, namun tidak wajahnya yang selalu sumringah. Seakan kesedihan tak pernah menghampirinya. Mungkin kata-kata Kartini yang menginspirasinya, “Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai”.
Dewi selalu membawa keceriaan bagi orang-orang di sekitarnya, meskipun pekerjaannya sebagai fotojurnalis menguras tenaga, pikiran, juga waktunya. Sering kali, Dewi harus bepergian dalam waktu cukup lama, sehingga harus berjauhan dengan suaminya. “Tidak pernah ada masalah, Hani (suami), selalu mendukung. Justru dia yang sering bantu pesankan tiket, kalau mendadak aku harus extend atau ketika harus pergi dan pindah ke tempat lain waktu motret di luar kota.”
Dewi, juga mempunyai peran dalam perjalanan hidup saya. Kami pertama bertemu, saat ia memotret saya dan keluarga, untuk majalah Muslimah tempatnya bekerja, pada tahun 2004. Kala itu, saya sampaikan padanya, “saya juga ingin menjadi fotografer seperti tante Dewi”. Itulah awal pertama saya memanggilnya ‘tante’. Saya tak ingat, apa jawabnya. Namun ketika kemudian ‘si tante’ mengirimkan beberapa hasil foto, ada portrait saya yang ia bubuhkan nama dan nomor telepon. Lebih kurang, dia bilang “katanya mau jadi fotografer, itu kartu nama untuk Iwan, biar jadi fotografer beneran “. Cukup lama saya tidak bertemu tante Dewi lagi setelah kejadian itu, tapi seperti sulap, hal itu kejadian.
Tak disangka, tiga belas tahun kemudian saya bekerja dalam satu project dengan tante Dewi. Kami, dan dua rekan lainnya, bekerja sama untuk mendokumentasikan acara tahunan salah satu klub mobil offroad papan atas Indonesia. Selama 15 hari, kami menelusuri surga tersembunyi pulau Sulawesi. Mengendarai mobil 4×4 memang merupakan salah satu hobi ‘si Tante’, yang juga sempat menjadi juara di event ‘Kartini Offroad’. Saya yang paling junior dalam bertualang, mendapat banyak pelajaran dari tante Dewi, dan juga kawan-kawan lainnya dalam perjalanan saat itu.
Selain memotret, Dewi juga senang difoto. Dia hobi ‘selfie’. Dewi kerap membagikan foto dan bercerita tentang kegiatan sehari-harinya, di dunia maya. Tempat dia sering melakukan keahliannya sebagai ‘tukang sulap’ lewat karya-karyanya. “Sekalian memberi kabar kepada teman-teman, juga keluarga”, kata Dewi, mengenai kesukaannya berbagi cerita. Media sosial, menjadi sarana silaturahmi bagi Dewi, yang mempunyai banyak teman di seluruh Indonesia.
April 2018, merupakan bulan spesial untuk tante Dewi yang hampir dua dasawarsa berjibaku di dunia ‘gambar diam’. Piala Anugerah Pewarta Foto Indonesia, yang merupakan ajang tertinggi para fotojurnalis Indonesia, diraihnya. Ia menang dalam kategori “Daily Life”, lewat karya berjudul ‘Atas Nama Cinta’, yang dibuatnya untuk media daring Beritagar. Bercerita tentang seorang perempuan berhijab, yang mencurahkan kasih sayangnya pada dua ekor anjing liar. Lagi-lagi Dewi membuat perubahan lewat karyanya, yang sebelumnya ramai di media sosial.
“Kembangkan network, buka mata dan telinga lebar-lebar, ada apa sih di dunia luar yang harus kita kabarkan. Tentunya kabar yang positif, yang bisa membuat orang lain terinspirasi. Bikin dunia lebih indah dengan karya fotomu.”, pesan tante Dewi, untuk saya. “Ketika bisa berbagi dan membuat perubahan lewat foto-foto yang aku buat, itulah pencapaian tertinggiku sebagai seorang fotografer, pungkasnya. Layaknya Kartini, tante Dewi Nurcahyani adalah seorang pembawa perubahan.